Media Sosial yang Menggerakkan
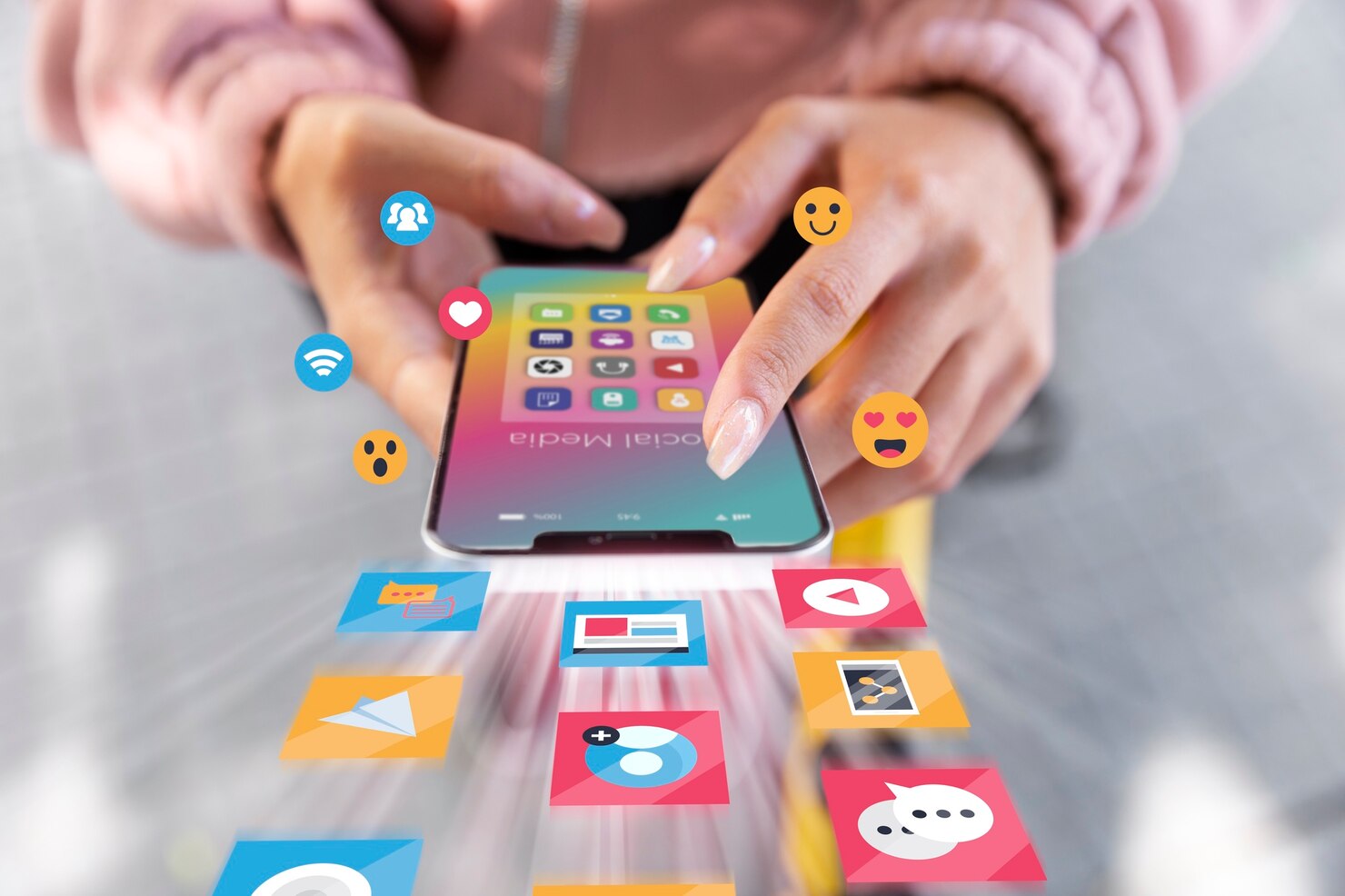
Jakarta - Sebanyak, 5.04 miliar manusia atau setara dengan 62.3% populasi manusia yang hidup hari ini, perlu mempertanyakan: apakah seleranya pada makanan merupakan otentisitas yang tumbuh dari dirinya sendiri?
Apakah pilihan destinasi wisatanya, merupakan keinginan yang bangkit dari pemahamannya sendiri? Apakah gaya berpakaian dan cara diri ditampilkan, merupakan kehendak asli dirinya?
Juga pandangan politik maupun perhatiannya pada peristiwa-peristiwa di sekitarnya, merupakan hasil perenungan yang terakumulasi dari batinnya sendiri?
Jumlah miliarian manusia yang disebutkan di atas, adalah angka terbaru yang diterbitkan oleh We are Social, Januari 2024. Institusi ini tiap tahun menerbitkan berbagai data dunia tentang keadaan digital sosial manusia. Juga infrastukturnya.
Sedangkan angka di atas disajikan pada bahasan Global Digital Headlines: manusia yang menggunakan internet berikut media sosialnya di seluruh dunia.
Dibanding seluruh pengguna internet dunia yang mencapai 5.35 miliar, jumlah pengguna media sosial, terpaut hanya 3.9%. Artinya hampir seluruh pengguna internet, merupakan pengadopsi media sosial.
Ini tentu merupakan wujud aktivitasnya, di dunia maya. Lima pilihan utama media sosial yang digunakan, mulai Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok maupun Telegram.
Seluruhnya menciptakan keterhubungan yang saling mempengaruhi. Adanya keterhubungan ini, mempengaruhi pembentukan selera, pandangan, hingga aktivitas yang mewarnai kehidupan global manusia.
Manusia jadi cenderung seragam. Karenanya, pertanyaan pada paragraf pertama, penting diajukan.
Tentu bukan hal baru, munculnya fenomena gerakan sosial yang mendunia, juga sentimen emosional yang mempengaruhi umat manusia, didahului konten media sosial.
Ini melahirkan berbagai istilah populer: activism, civic advocacy, grassroots, political participation. Juga slactivisme.
Revolusi 2010 di Timur Tengah yang dikenal sebagai Arab Spring contohnya, dapat disebut sebagai bukti awal kekuatan media sosial. Kala itu, dengan tersebarnya kemarahan yang dimediasi Twitter, terpicu gelombang revolusi pergantian kepemimpinan yang luas.
Pengaruhnya hingga mencapai 16 negara, termasuk Mesir. Revolusi dimulai oleh perselisihan Tarek El-Tayeb Mohamed Bouazizi seorang pedagang keliling buah-buahan di Tunisia dengan polisi pamong praja setempat.
Perselisihan diakhiri dengan aksi bakar diri Bouazizi, yang membangkitkan protes luas masyarakat Tunisia. Informasi yang terbingkai lewat Twitter, Bouazizi yang sekedar mencari rezeki penyambung hidup, dicederai aparat penguasa setempat dan mati terbakar.
Berbekal modal akumulasi ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, peristiwa Bouazizi jadi momentum suksesi kepemimpinan nasional.
Bukan dengan cara baik, tapi lewat unjuk rasa yang menekan. Gulungan perasaan yang semula termediasi media sosial, meluber jadi gerakan aktual di seluruh penjuru Tunisia.
Ben Ali berhasil digulingkan pada 14 Januari 2011, setelah 23 tahun berkuasa. Suksesi yang termediasi oleh Twitter ini, sentimennya menjalar jauh, hingga ke luar Tunisia.
Sepuluh tahun berselang, tahun 2020, di belahan dunia yang lain Amerika Serikat, terjadi peristiwa yang membawa kepahitan bagi Tim Pemenangan periode ke-2 kepresidenan Donald Trump.
Baca Juga: Realitas Cair Zaman Artificial Intelligence
Peristiwa pahit ini, juga digerakkan media sosial. Kali ini yang menggerakkan, para penggemar K-Pop dengan akun TikTok-nya. K-Popers bersepakat tak menghadiri pidato Trump di Tulsa, Oklahoma, padahal ribuan tiket telah diborong komunitas ini.
Tak kurang dua puluh ribuan tiket yang disediakan sesuai kapasitas arena pidato, terjual habis. Namun yang hadir tak lebih dari seperempatnya. Alhasil Trump berhadapan dengan arena pidato kosong, tak menggairahkan.
Kursi-kursi tak diisi pembeli tiket, yang semula dikira sebagai pendukungnya. Para K-Popers memboikot Trump lantaran sering bersikap rasis, misoginis dan diskriminatif. Taring keterhubungan yang terbentuk lewat media sosial, kembali memakan korbannya.
Hari ini, di tengah Aksi Militer Israel pada penduduk Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, berlangsung Gerakan BlockOut 2024. Gerakan yang diprakarsai akun TikTok @BlockOut2024, ini bekerja dengan cara membagikan daftar nama pesohor dunia, yang dianggap tak menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina.
Tak berhenti sampai di situ, pembagian daftar nama diikuti dengan ajakan untuk melakukan blocking beramai-ramai, akun media sosial para pesohor. Nama-nama sekelas Taylor Swift, Ariana Grande, Kim Kardashian, Selena Gomez, Rihana, Sam Simth, Beyonce, termasuk juga Justin Beiber dan istrinya, disebut sebagai pesohor yang perlu di-blocking.
Inisiasi #BlockOut 2024 yang dilangsungkan sejak 6 Mei 2024 bersamaan dengan Met Gala 2024, juga serangan Israel ke Raffah bergulir mendunia. Ini terindikasi dari beredarnya nama-nama pesohor lokal yang tak Pro Palestina, dari berbagai negara dunia.
Jelas dari keserempakan waktunya, merupakan gerakan #BlockOut 2024, yang telah menjalar ke seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah gerakan sosial lewat media sosial, semacam #BlockOut 2024 ini, manjur mengubah keadaan? Apakah gerakan terbentuk oleh kesadaran yang otentik, atau sebatas emosi yang menular?
Terhadap pertanyaan ini, Dalainey Gervais, 2021 lewat tulisannya yang dimuat di The Medium, dengan judul panjang “The Effectiveness of Social Media Activism: Social Media Platforms Help Raise Awareness on Important Issues Worldwide”, menyepakati munculnya gerakan sosial yang dibangun lewat media sosial.
Gervais dengan mengutip pendapat Jillian Sunderland, seorang Mahasiswa Doktoral Bidang Sosiologi di SSHRC Joseph-Armand Bombardier Canada Graduate Studies Program di University of Toronto, menandaskan: aktivisme media sosial memberikan perangkat bersikap bagi individu.
Selama ini individu tak punya sarana untuk menyuarakan keterlibatan sosialnya, yang penting. Lewat media sosial, masyarakat juga dapat mempengaruhi pihak lain lewat percakapan.
Ini berguna dalam mengungkap kebenaran kepada pihak yang berkuasa. Seluruh rangkaian kerja, bermanfaat bagi komunitas yang terpinggirkan, dalam menyampaikan pandangannya atas dunia.
Pandangan yang disusun dari perspektifnya sendiri. Persoalan sosial yang terjadi, dapat terdeskripsikan secara tepat oleh komunitas. Media sosial memberi perangkat menyuarakan keterbungkaman, sehingga dunia tahu: telah terjadi persoalan sosial yang nyata.
Gerakan sosial yang termediasi media sosial sebagaimana Arab Spring, maupun pemboikotan Pidato Donald Trump, #BlockOut 2024 mempunyai sisi utama kekuatan yang menggerakkan.
Sisi utama yang menggerakkan itu jadi landasan bersama untuk bergerak. Pada Arab Spring, ada rasa ketidakadilan akumulatif yang meluas. Warga negara menyimpan rasa kesal terhadap ketakadilan yang terus dialami.
Jika ketakadilan yang terus berlangsung belum menyebabkan warga negara bergerak, lantaran menanti momentum yang tepat. Ketakadilan yang kasat mata, peristiwanya mudah dicerna, yang kemudian disepakati sebagai ketakadilan yang harus dilawan.
Momentum Bouazizi membakar diri, memenuhi persyaratan itu. Seluruhnya terbingkai sebagai sikap sewenang-wenang yang makin tak dapat ditoleransi.
Senada dengan gejala di atas, pada pemboikotan Pidato Donald Trump oleh para K-Popers, kelompok ini merasakan arogansi Donald Trump yang kian tak terbendung. Kebiasaan merendahkan perempuan di depan publik, pandangannya yang rasis membuat malu warga negara penjunjung hak azasi manusia, juga komentar-komentarnya yang homofobik.
K-Popers yang menyadari kekuatan jejaringnya, bersepakat membalas Trump, dengan mempermalukannya. Gerakan ini menyadarkan Warga Amerika Serikat yang lebih luas, ada perilaku buruk Sang Presiden, yang harus dikoreksi.
Sedangkan pada #BlockOut 2024, selain terdapatnya perasaan buruk terhadap Israel sebagai landasan gerakan bersama, juga digulirkan dengan memilih momentum emosional: setelah berlangsungnya Met Gala 2024, yang penyelenggaraannya bertepatan dengan pengemboman Raffah-Palestina oleh Israel. Ini menyulut kemarahan seluruh dunia.
Terpampang gamblang lewat berbagai media, Met Gala 2024 dihadiri para pesohor dunia. Ini kemudian dibingkai sebagai tak pedulinya kelompok ini, atas penderitaan yang terjadi. Para pesohor tetap sibuk berpesta, bersamaan dengan kesengsaraan yang sedang terjadi.
Juga, sikap jelas para pesohor dalam mendukung Palestina, tak ditampilkan. Sedangkan sikap pro ini, diharapkan mampu menggerakkan warga dunia pendukung para pesohor secara massif.
Tujuannya, agar makin kuat menekan Israel menghentikan aksi militernya. Lewat gerakan blocking media sosial-media sosial para pesohor, mereka dipaksa segera bersuara. Atau dilakukan cancel culture.
Tentu saja, bagi kaum yang meraih dukungan lewat media sosial, gerakan blocking media sosial, adalah petaka yang dapat menamatkan karirnya. Lewat gerakan ini, sikap pesohor dipaksa muncul.
Namun dengan seluruh pencapaian gerakan yang diraih, pertanyaan berikutnya: benarkah para pemilik akun media sosial dalam menjalankan gerakannya dilandasi pemahaman yang utuh pada activism yang diperjuangkannya?
Atau sekadar jadi bagian gulungan emosi, yang menular lewat media sosial? Sebab jika hanya gulungan emosi yang menular, sasaran boikot yang telah terpengaruh hidupnya, tak lebih hanya jadi korban emosi tanpa rasionalitas. Tanpa rasionalitas, gerakan tak lebih sekedar gaya hidup sementara. Namun akibat yang harus ditanggung, bersifat permanen. Sungguh malang.
* Penulis merupakan Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital sekaligus pendiri LITEROS.org
* Isi artikel merupakan pendapat penulis, bukan merupakan pandangan Urbanasia




