Wajah Budaya di Tengah Ekologi Media Digital
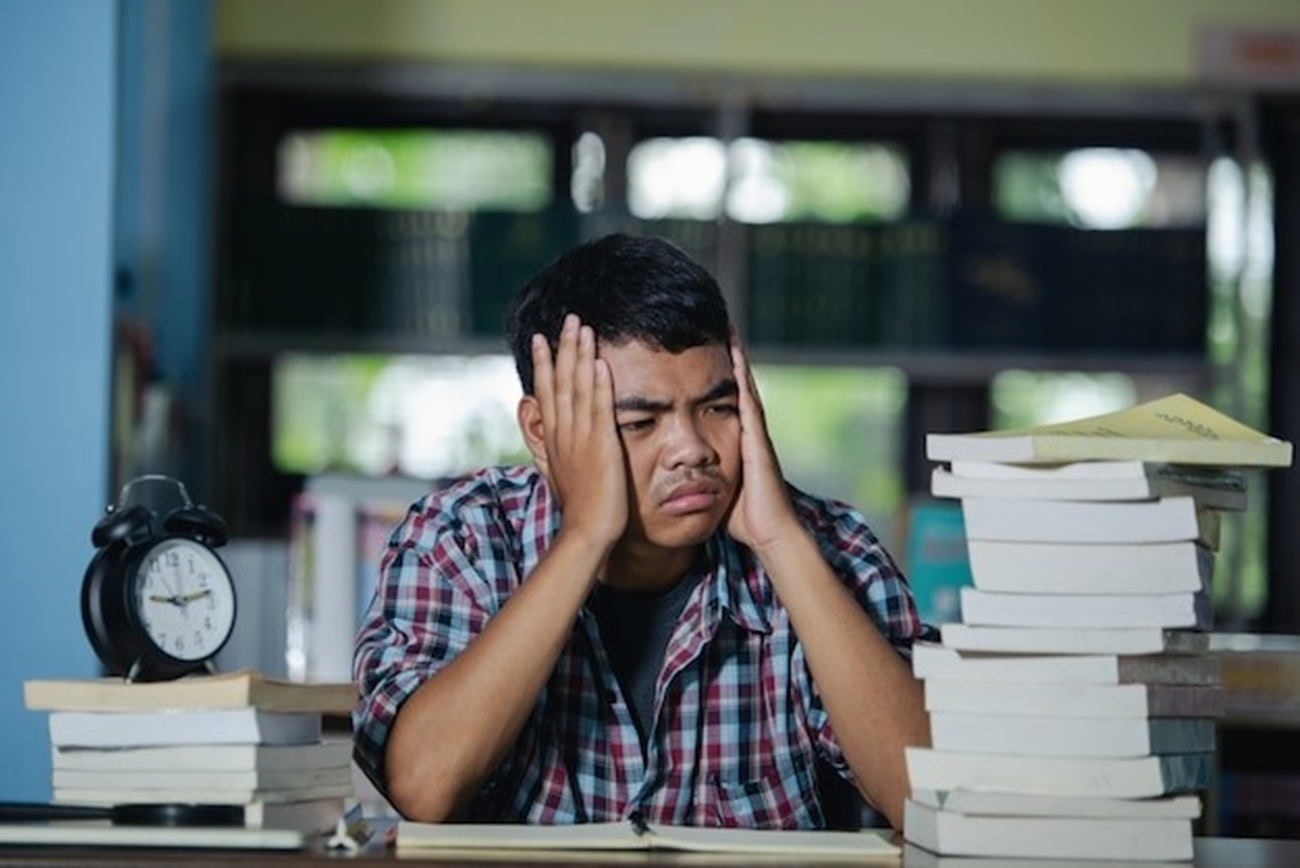
Jakarta - Sebuah tulisan lama oleh Fahri Zulfikar, 2021, yang dimuat di detikcom, berjudul '87 Persen Mahasiswa RI Merasa Salah Jurusan, Apa Sebabnya?', mengungkap gejala tak sinkronnya pilihan studi yang dijalani mahasiswa, dengan cita-cita sejatiinya. Angka 87% yang dikutip berdasar penelitian Irene Guntur, seorang psikolog pendidikan dari Integrity Development Flexibility (IDF) menyebut: pengaruh teman, mendengar terlalu banyak saran, menjalani kehendak orang tua, hingga tawaran beasiswa, merupakan aneka faktor pembelok cita-cita mahasiswa.
Akibat dari keadaan itu, ada tendensi perkuliahan yang tak dinikmati, walau perguruan tingginya bergengsi. Juga tak sesuainya karier yang ditempuh, dengan studi yang dijalani saat masih mahasiswa. Kuliahnya di mana, kiprahnya entah apa setelah lulus. Perkuliahan tak mengantar para peserta didik menempa diri, masuk ke jenjang karier. Cita-cita dipaksa belok, akibat aneka penyebab.
Sayangnya dari seluruh faktor pembelok yang disampaikan Sang Ahli Pendidikan di atas, tak menyebut peran media dalam mempengaruhi cita-cita para peserta didik. Bisikan media nyata mempengaruhi pilihan studi, cita-cita, bahkan persepsi tentang masa depan. Media juga mampu membelokkan cita-cita, yang sejak lama digenggam. Media secara luas mampu membangun realitas yang dijalani umat manusia.
Kilas balik balik pada Gen X, kelompok yang saat ini ada di usia sekitar 44-58 tahun, lazim dengan cita-cita menjadi dokter, insinyur atau diplomat. Ini lantaran media saat itu mengilustrasikan, betapa hebatnya profesi-profesi di atas. Menjadi salah satu di antara ketiganya jadi indikasi keberhasilan, orang yang hidup di tahun 70-80an. Sedangkan Gen Milenial yang usianya saat ini ada di rentang 28-43 tahun, menginginkan dirinya tampil sebagai bintang radio, sebagai finalis pencarian bakat di televisi atau diberitakan memenangi Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR), di koran. Ini lantaran, siapa pun yang berhasil tampil di media massa pada tahun 80-90an itu, bakal jadi tersohor. Tentu saja harapan berikutnya, memperoleh kemudahan meraih rejeki, berbekal pengenalan yang luas.
Lalu apa cita-cita Gen Z, yang saat ini ada di kisaran usia 13-27 tahun? Menjadi youtuber, content creator, atau influencer. Seluruhnya merupakan cita-cita yang biasa diucapkan, hari ini. Jika pada generasi ini ditanya, mengapa itu pilihannya? Mungkin tak diperoleh jawabannya yang jelas. Sebab memang seluruhnya dipengaruhi kelaziman. Kelaziman yang ditularkan media yang hidup di sekitarnya.
Baca Juga: Ribuan Tanya soal Artificial Intelligence
Operasi pengaruh media pada berbagai aspek kehidupan, banyak dibahas. Salah satunya berdasar uraian Marshall McLuhan. Filsuf asal Kanada ini menuliskan gagasan lewat bukunya, yang berjudul “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man”. Buku tersohor yang terbit pada tahun 1962. Pada pokoknya McLuhan menyebutkan, sejak hadirnya mesin cetak Gutenberg di tengah peradaban, terjadi lompatan cara manusia dalam memandang realitas. Seluruhnya terjadi secara total. Realitas yang semula dihadirkan sebagai budaya lisan, bergeser terepresentasi sebagai budaya tulis.
Ini kemudian kembali bergeser, menjadi budaya visual, lantaran kehadiran media elektronik. Semakin media berkembang, terjadi perubahan yang berciri penyeragaman bahasa, saat media menyajikan informasi. Implikasinya, informasi dapat diakses oleh khalayak yang luas, berikut pengaruhnya yang tersebar bebas. Pada gilirannya, terciptanya masyarakat yang lebih terstruktur dan terorganisir. Pengejaran pengetahuan dan individualisme menjadi norma yang mengemuka. Media elektronik, televisi maupun radio, menciptakan dunia yang terhubung. Ini yang kemudian lazim disebut sebagai global village. Menyebar luas, namun seragam.
Konsep senada tentang pengaruh media pada pembentukan persepsi, pemahaman, perasaan maupun nilai manusia, diungkapkan oleh Neil Postman, 1985. Seluruhnya termuat dalam bukunya yang berjudul, “Amusing Ourselves to Death”. Di Indonesia, buku Postman ini, diterjemahkan sebagai “Menghibur Diri Sampai Mati”, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, 1995. Pada pokoknya Postman menyebutkan, interaksi manusia dengan media dapat memfasilitasi atau menghalangi peluang manusia untuk menjalani hidup. Termasuk dalam memilih cita-cita yang hendak diraihnya. Seluruh pikirannya ini, lazim disebut ekologi media. Sebuah konsep yang menyiratkan pemahaman tentang lingkungan, terdiri dari struktur, konten, dan dampaknya, terhadap manusia. Media yang merupakan unsur lingkungan manusia adalah sistem simbol yang kompleks, mampu mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, hingga munculnya perilaku tertentu pada manusia.
Sayangnya ungkapan pemikiran tentang ekologi media di atas, sebatas interaksi antara media dengan manusia, dan budaya sebagai hasilnya. Budaya yang dihasilkan seakan-akan bebas nilai. Netral, apa adanya. Bahwa dalam realitasnya budaya yang terbentuk tak bebas nilai ikut kehendak pihak tertentu yang punya kepentingan tak jadi perhatian. John McGee, 2023, dalam “Why 60 Years Later Marshall McLuhan’s Ideas are as Relevant as Ever”, mengungkap kritik tersebut. Pikiran McLuhan masih terasa relevansinya hingga hari ini. Peran media mempengaruhi peradaban, masih terbukti. Ini walaupun telah berjarak 60 tahun, dari saat pertama pengungkapannya. Namun asumsinya tetap: media yang bebas nilai sebagai pembentuk budaya.
Adakah unsur lain yang mempengaruhi interaksi manusia dengan media dalam membentuk budaya? Mengapa jika manusianya tetap, dan hanya bentuk medianya yang berubah, dapat mempengaruhi budaya yang dibentuk? Apakah determinasi lebih ditentukan oleh manusia atau medianya? Lewat pertanyaan-pertanyaan inilah, ungkapan tersohor Marshall McLuhan, The Medium is The Messeage, memperoleh relevansinya.
Ini penjelasannya. Dari masa ke masa, corak pesan sangat ditentukan mediumnya. Ketika berhadapan dengan medium buku di era mesin cetak, pesan yang dapat dimuat sesuai kemampuan mesin mencetak buku. Bentuknya, pesan teks yang panjang maupun visual yang ilustratif. Pengetahuan dapat tersebar dan pemahaman mengalami penyeragaman. Manalaka zaman berubah dan medium berkembang jadi elektronik, pesan yang dapat ditransmisi sebagai gelombang elektromagnetik, yang dapat dimuatkan pada medium. Wujudnya teks, audio, visual, hingga video. Cirinya mudah dipancarkan, mampu menjangkau khalayak luas, makin menciptakan penyeragaman pemahaman yang masif. Hari ini, ketika manusia hidup di tengah medium digital, pesan-pesan yang berbentuk kode-kode binerlah yang beredar. Cirinya pendek mengikuti kode 0-1-1-0, intensif, dapat diakomodasi berbagai bentuk pesan: teks, audio, visual, video, maupun gabungan seluruhnya, yang diubah ke kode-kode biner. Jelas, pesan dideterminasi oleh medium. Sehingga hasil akhirnya, pesan itulah mediumnya.
Namun uraian di atas belum mampu menjelaskan: tak bebas nilainya budaya yang terbentuk. Bahkan yang terjadi di era digital. Dengan menggunakan hasil penelitian yang dilakukan Kevin Kelly, 2016 dan dimuat pada bukunya yang berjudul “The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future”, diperoleh kenyataan, semua perusahaan media, musik, buku, film, berita, hanya memperoleh berpenghasilan dari perhatian yang diberikan khalayak, sebesar rata-rata US$3/ jam. Nilai ini konstan selama 20 tahun. Kelly melakukan penghitungan sejak tahun 1995, 2010 dan 2015. Metode yang digunakannya pun sama. Hasilnya $3,08, $2,69, dan $3,37. Berada di kisaran US$ 3. Ini artinya nilai perhatian yang diberikan konsstan. Maka untuk menembus stagnannya nilai keuntungan yang dihasilkan pengembang media, cara yang dapat ditempuh adalah: menjual khalayak media. Sebab khalayak pengguna media, punya 2 unsur komodifikasi: data dan perhatian.
Yang kemudian dilakukan pengembang media, menciptakan pesan yang mampu menyerap perhatian pengguna. Seluruhnya dikemas untuk dapat mempertahankan perhatian, agar tak beralih ke aktivitas lain. Dari bertahannya perhatian, jumlah waktunya dijual kepada para pengiklan. Pesan-pesan yang diunggah di media disisipi iklan yang mendorong pembelian. Penjualan waktu perhatian ini, menghasilkan keuntungan bagi pengembang media. Akan halnya interaksi saat perhatian diberikan khalayak, diolah sebagai data perilaku khalayak. Juga merupakan material yang berharga, dalam menyusun iklan yang kontekstual bagi khalayak.
Seluruh sirkulasi ekonomi yang terjadi, lazim disebut ekonomi perhatian, the economic of attention. Hanya saja implikasinya tak sebatas menggelumbungnya pundi-pundi harta para pengembangan media. Muncul budaya yang didorong corak ekonomi yang dikembangkan. Budaya yang didasarkan nilai perhatian. Berciri, hanya peduli pada sesuatu yang langka terjadi, menyerap seluruh perhatian pada peristiwa yang dinilai kecil peluangnya untuk terulang. Itulah ekologi media hari ini. Mendorong peradaban yang memaksa diberikannya perhatian. Seluruhnya karena khawatir tak terperbaharuinya pengetahuan, Juga ketakutan untuk ketinggalan informasi, fear of missing out. FOMO, perilaku kontroversial yang langka berulang, antimainstream, jadi budaya utama pada ekologi media hari ini. Inikah keadaan yang dicita-citakan para pengguna media hari ini?
*) Penulis adalah Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital
**) Tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis, bukan pandangan Urbanasia




