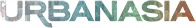URtopic: Susahkah Menjerat Pelaku Kekerasan Seksual?

Jakarta - Dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) sebut saja Melati mungkin hanya satu dari banyak kasus serupa di Indonesia. Tak banyak yang berani speak up. Alasannya banyak. Ada yang takut, malu, dan bahkan ada yang pesimis kasusnya bisa diselesaikan di pengadilan.
Tapi benarkah sesusah itu menjerat pelaku kekerasan seksual? Pakar hukum pidana Prof Dr Mudzakir SH, MH menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus pelecehan seksual lebih dikenal dengan perbuatan cabul alias pencabulan, guys!
"Istilah pelecehan seksual dalam KUHP dikenal dengan namanya adalah pelanggaran kesusilaan publik, kejahatan kesusilaan seksual atau pencabulan," jelas Mudzakir kepada Urbanasia, Rabu (22/4/2020).
Mudzakir mengkategorikan, perbuatan pencabulan termasuk dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP. Jadi, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan.
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun," jelas Mudzakir.
Disamping itu Mudzakir pun menggarisbawahi, yakni pasal perbuatan pencabulan dan pemerkosaan memiliki konteks yang berbeda.
"Kalau percobaan pemerkosaan itu berbeda, pasalnya itu adalah Pasal 53 KUHP yang dihubungkan dengan tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP. Jadi, agak berbeda dalam konteks ini," terangnya.
Menurutnya, jika pelaku sudah ada niatan untuk bertindak memperkosa tapi tidak berhasil akan masuk ranah hukum Pasal 53 juncto Pasal 285 KUHP Sebaliknya, kalau sudah melakukan pemerkosaan dan merugikan korban, masuk dalam ranah hukum Pasal 285 KUHP saja.
"Jika pemerkosaan terjadi maka masuk Pasal 53 KUHP. Sedangkan kalau belum terjadi perkosaan padahal sudah berniat memperkosa tapi gagal, maka pasalnya masuk pasal 53 juncto pasal 285 KUHP," tutur Mudzakir.
KUHP memberikan hukuman sampai dengan dua tahun delapan bulan penjara serta hukuman denda atas tindakan percobaan perkosaan. Sementara, dalam hal kekerasan yang berujung pada hubungan seksual, hukumannya meningkat sampai dengan 12 tahun penjara loh.
Sedangkan bicara soal regulasi kampus dalam menanggapi kasus pencabulan ataupun pemerkosaan, Mudzakir mengatakan regulasi kampus saat ini hanya sampai tindakan preventif saja.
"Kalau terjadi tindakan pelecehan seksual entah itu dari mahasiswa ke mahasiswa, dari dosen ke mahasiswa, dan sebagainya itu, sebaiknya harus ada tempat penyelesain yang intinya kalau orang yang membahayakan terhadap orang lain dalam bidang seksual sebaiknya mereka dikeluarkan dari kampus," ujarnya.
Terakhir, dari sisi korban, Mudzakir mengatakan korban pencabulan atau perkosaan memiliki peran penting dalam menjerat hukuman kepada pelaku.
"Pilihan untuk lapor maupun tidak lapor itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak korban. Jadi kampus hanya sebatas mengeluarkan pelaku disebabkan karena dapat merusak citra kampus dan membahayakan keselamatan orang lain di bidang seksual," tukasnya.
Lalu, bagaimana sikap UI terkait kasus dugaan perkosaan yang menimpa mahasiswi sebut saja namanya Melati? Menurut BEM UI, kasus itu kini ditangani HopeHelps, sebuah lembaga pencegahan san penanganan kekerasaan seksual di lingkungan kampus.
Namun dari sejumlah kasus yang pernah terjadi, belum ada satupun pelaku yang mendapatkan sanki berat seperti dikeluarkan atau DO. Hal ini pun menjadi salah satu keprihatinan BEM UI yang memandang pihak kampus kurang tegas dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual.
BEM UI pun merilis sikap yang berisi dua rujukan untuk penanganan kekerasan seksual di kampus, yakni Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia (SIPDUGA UI) dan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2) yang dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus Kekerasan Seksual di lingkungan UI.
"Dalam hal ini, UI seharusnya membuat sebuah regulasi yang diwujudkan dalam bentuk layanan pengaduan/crisis center khusus Kekerasan Seksual di lingkungan kampus," tulis dalam rilis sikap tersebut.
Menurut aliansi BEM se-UI, yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan UI justru kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang dapat dilihat dari inkompetensi regulasi pada Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MWA UI Nomor 008 Tahun 2004.
Hal itu karena Pasal 8 menyebutkan bahwa Warga Universitas Indonesia dilarang untuk ‘melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual’. Pada pasal ini, deskripsi ‘pelecehan seksual’ tidak dapat meliputi dimensi kekerasan seksual yang sangat luas.
"Ditambah lagi, ketidakjelasan ketentuan sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap Ketetapan MWA menjadikan setiap bentuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut menjadi semakin samar. Hal itu terlihat dalam pasal 9 Peraturan MWA nomor 8 tahun 2004 yang tidak menjelaskan secara rinci akan sanksi apa yang didapatkan oleh pelaku. Hal ini membuat pelaku dalam kasus kekerasan seksual bisa saja mendapatkan sanksi yang “tidak sesuai” dengan keadilan menurut pandangan warga UI," ungkap rilis sikap BEM UI.
"Oleh karena itu, diperlukan upaya revisi peraturan ini guna memperjelas jenis sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus UI," lanjut rilis itu.
Selain itu, menurut rilis sikap tersebut, dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan lain yang membuat mekanisme SIPDUGA UI tidak dapat menjadi solusi atas fenomena kekerasan seksual di Lingkungan UI. Pertama, penggunaan istilah pelecehan seksual atau asusila sebagaimana telah disinggung sebelumnya, frasa tersebut dianggap tidak mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
Kedua, mekanisme pelaporan SIPDUGA UI tidak mengatur secara khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual sehingga dikhawatirkan penerimaan laporan dan penindak lanjutannya disamakan dengan bentuk-bentuk pelanggaran lain. Hal tersebut menjadi masalah karena pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual membutuhkan pendekatan lain dalam melakukan investigasi seperti wawancara terhadap pelapor dengan menggunakan etika dan pendekatan psikologis.
Ketiga, pengambilan keputusan dalam mekanisme pelaporan SIPDUGA UI hanya dilakukan oleh tim penyelesaian tanpa melibatkan pelapor. Hal tersebut dapat ditinjau dari rangkaian mekanisme SIPDUGA UI setelah lulus verifikasi berkas yang melibatkan tiga tim yaitu tim administrasi, tim penyelesaian, dan tim investigasi.
Dalam buku panduan UI ternyata hanya menyebutkan penanganan kasus tindakan asusila dan pelecehan seksual melalui pelaporan pelaku ke Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), pemanggilan orang tua pelaku, pembuatan surat pernyataan bersalah dan tidak mengulangi. Sedangkan, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan zina akan dilaporkan ke pihak kepolisian.
"Penggunaan terminologi zina tersebut dapat menimbulkan sesat pikir yang mengaburkan hakikat kekerasan seksual. Sehingga, kami menilai prosedur tersebut belum memadai sebab belum mencakup mekanisme pemulihan korban seperti pendampingan psikologis," jelas ailiansi BEM se-UI dalam rilis sikap tersebut.