Ribuan Tanya soal Artificial Intelligence
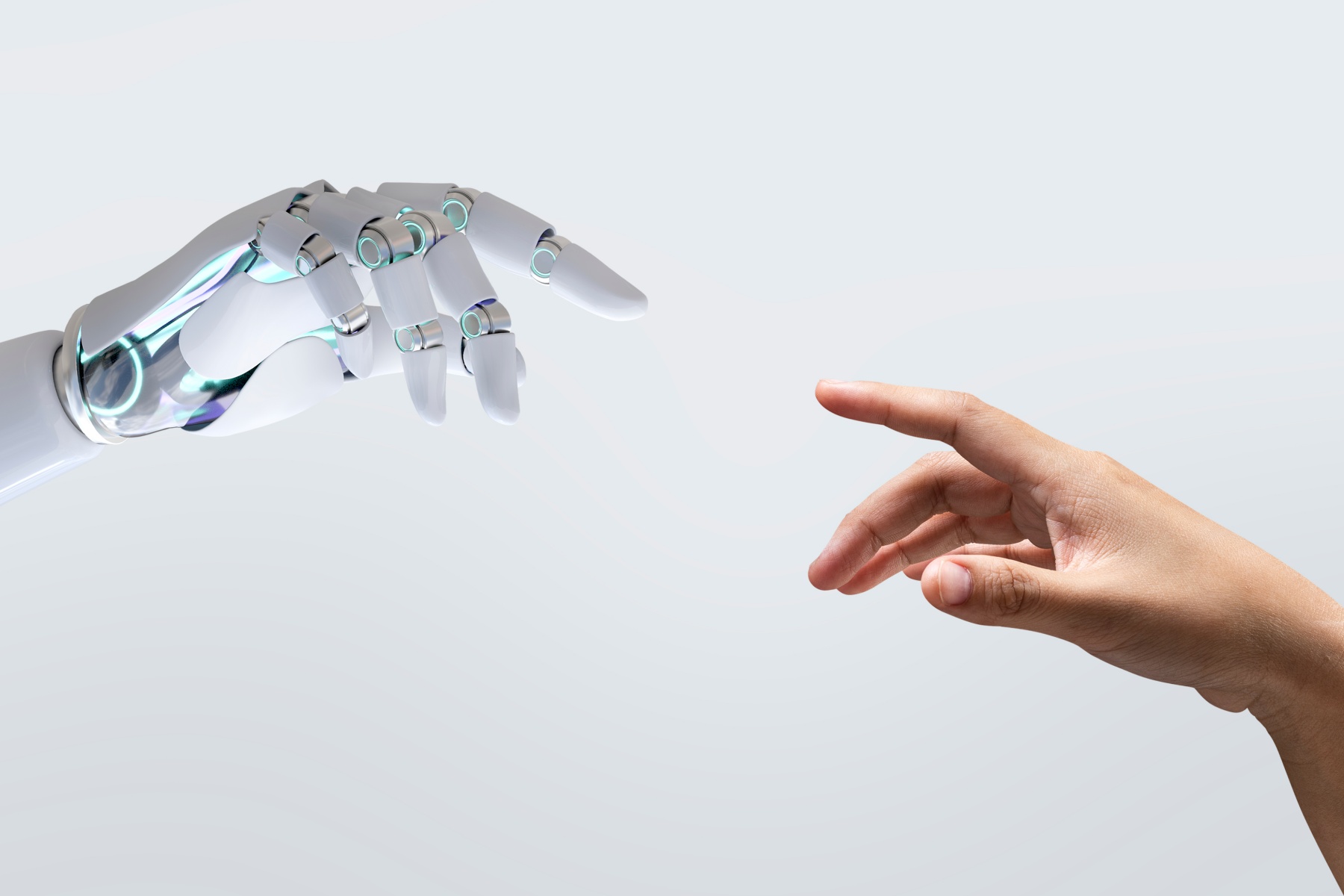
POPULARITAS artificial intelligence (AI), yang terbawa oleh peluncuran ChatGPT, di penghujung tahun 2022, mendudukannya sebagai produk baru dalam persepsi khalayak. Sebagai produk baru, perhatian, pembicaraan maupun uji coba yang demikian massif, melahirkan berbagai pertanyaan.
Ketakpahaman keragu-raguan maupun kekhawatiran yang mendera, menjelma jadi ribuan tanya. Spektrumnya mulai substansi teknologi itu sendiri, hal yang harus disiapkan untuk menghadapi era AI, hingga pertanyaan soal etika pemanfaatannya.
Pertanyaan soal substansi teknis, ada di seputar kemampuan yang ditawarkan AI dalam menunjang produktivitas kerja. Juga investasi untuk mengadopsi teknologi, berikut syarat teknis maupun pengetahuan yang harus dimiliki.
Seluruhnya agar AI dapat dimanfaatkan dengan optimal. Tak jarang pula terselip pertanyaan menyangkut batas kemampuan yang dapat dijangkau AI. Mengemuka sebagai bentuk kekhawatiran tersingkirnya manusia oleh teknologi yang dianggap sakti ini.
Untuk pertanyaan yang menyangkut hal-hal yang harus disiapkan, berikut mitigasinya jika AI ‘benar-benar’ menyebabkan irelevansi di dunia kerja, dalam bentuk: pekerjaaan macam apa yang bakal digantikan AI, jumlah tenaga kerja yang bakal tergantikan AI, hingga hal yang harus disiapkan individu, dunia kerja, maupun negara, untuk mengantisipasi gejolak sosial. Seluruhnya, akibat hadirnya keadaan yang diduga mengerikan, tumpukan pengangguran akibat irelevansi oleh AI.
Yang pelik dan tak mudah ditentukan jawabannya, pertanyaan-pertanyaan terkait etika seiring massifnya penggunaan AI. Ini misalnya, saat AI mampu memproduksi citra persona tertentu. Lewat kemampuan ini, AI dapat digunakan untuk menciptakan tiruan perilaku seseorang. Tampilannya sangat identik. Jikapun ada perbedaan, tak cepat dikenali. Ini lantaran perbedaannya sangat samar, tak mudah ditemukan oleh mata biasa.
Teknologi berbasis AI yang lazim disebut sebagai deepfake ini, berpeluang menampilkan orang tertentu: bernyanyi, berkelakar, bercakap-cakap interaktif hingga berpidato mempengaruhi khalayak banyak. Dapat dimanfaatkan untuk tujuan hiburan hingga tujuan yang serius, mampu mempengaruhi keputusan orang banyak.
Implikasinya, mulai yang tak ada kaitannya dengan aspek etis sama sekali. Namun pada penggunaan tertentu, justru sangat berat kadar etisnya. Pertanyaan untuk bagian terakhir itu misalnya, ‘Bagaimana status sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh dorongan pernyataan tiruan, bahkan palsu? Apakah keputusannya harus dibatalkan atau dibiarkan saja?’.
Lewat artikel berita yang ditulis Ewan Palmer, dan dimuat pada Newsweek.com, 14 Maret 2022, berjudul: ‘Donald Trump Deepfake Shows Ex-President Joining Russia's Version of YouTube’, dapat dibayangkan implikasi etis itu.
Artikel itu memuat kutipan mantan Presiden Amerika, Donald Trump, kurang lebih: ‘Saya sudah lama tidak ada, di media sosial, tapi saya tidak menghilang. Saya tidak menyerah, kita tidak bisa dibungkam. Hal utama adalah memilih momen yang tepat. Dan sekarang, momen itu, telah datang. Maaf para pecundang dan pembenci, tapi saya di sini lagi. Saya telah memilih platform di mana kebebasan berbicara tidak ditekan. Saya telah menemukan ruang untuk berinteraksi. Halo Rusia, halo RuTube’.
Ada beberapa konteks yang harus disertakan dalam memaknai unggahan deepfake Donald Trump di atas. Dari sisi pengunggahannya, dipilih di seputar bulan Maret 2022. Ini adalah waktu, yang tak lama berselang setelah Rusia menyerbu Ukraina di hari pertama, 24 Februari 2022.
Mengiringi serbuan itu, terjadi aksi hengkangnya berbagai brand produk dari Rusia dan pemutusan hubungan kerja brand Rusia dengan Amerika. Ucapan Donald Trump yang beralih menggunakan RuTube, seakan justru bersekutu dengan Rusia. Tak masalah baginya, Rusia menyerbu Ukraina. ‘Ya sekedar’ menggunakan media sosial saja. Tak ada urusannya dengan kebijakan politik negara.
Padahal yang sesungguhnya terjadi, Presiden Joe Biden yang sedang berkuasa ~mantan seteru Donald Trump di pemilihan Presiden Amerika~ punya kebijakan yang berbeda: memosisikan Amerika sebagai sekutu Ukraina, dan memusuhi Rusia.
Dalam unggahan itu pula, konteks sebagai mantan presiden ditonjolkan. Seluruhnya tentu menjadikan lekat konotasinya dengan haluan kebijakan politik negara. Bagaimana mungkin antara presiden dengan mantan presiden, punya haluan politik negara yang berbeda? Tentu akan jauh maknanya, jika dalam unggahan deepfake rakyat biasa yang ditampilkan.
Konteks lain yang menyertai unggahan itu, dibekukannya beberapa akun media sosial Donald Trump. Seluruhnya lantaran ucapan-ucapan Sang Mantan Presiden ini, memicu terjadinya pendudukan Gedung Capitol, berikut kerusuhan besar yang tak mudah dikendalikan.
Pendukung Donald Trump menolak hasil pemilu, lantaran dianggap mengandung kecurangan. Kecurangan yang menyebabkan gagalnya Sang Presiden, mempertahankan tampuk kursi kekuasaan di periode kedua. Unggahan deepfake mengolok kebijakan berbagai pengembang platform, sebagai telah tercederainya kebebasan berekspresi warga negara Amerika. Suatu bentuk kebebasan yang jadi bukti keagungan demokrasi Amerika.
Makna keseluruhan dari unggahan deepfake, membangun persepsi publik Amerika maupun masyarakat dunia, terhadap posisi Donald Trump. Seakan berhadap-hadapan dengan berbagai posisi Amerika. Posisi itu menyangkut kebijakan politik Amerika, maupun norma kebebasan berpendapat yang dicabut, akibat terlemparnya Donald Trump dari beberapa platform media sosial.
Posisi yang berhadapan ini, berpeluang mengundang reaksi maupun sentimen pendukung Sang Mantan Presiden yang jumlahnya masih besar. Jika keadaan berlanjut, tak tertutup kemungkinan terjadinya segregasi sosial antar warga ~Pro Trump vs Kontra Trump~ di negara itu, untuk pernyataan yang tak pernah ada.
Tak jadi soal jika memang Donald Trump punya pendapat yang senada dengan unggahan deepfake. Alih-alih keadaannya demikian, seluruhnya hanya hasil simulasi berbasis teknologi. Warga negara berseteru masing-masing membela junjungannya, ternyata untuk pernyataan yang tak ppernah diucapkanmnya.
Nampak, unggahan deepfake bukan semata hasil kemampuan teknologi. Penggunaan yang tak disertai etika, memancing ketakpastian kebenaran yang diyakini khalayak. Terbentuknya realita akibat unggahan yang tak otentik, bahkan palsu hanya menghadirkan keadaan yang kisruh, tak dapat dipercaya. Ada konsekuensi etis bagi pihak yang memanfaatkan AI untuk keperluan semacam ini.
Permasalahan etis yang juga mengundang banyak perdebatan, muncul di dunia akademis. Layakkah produk AI, termasuk ChatGPT digunakan di lingkungan akademis? Konteks pertanyaan ini akibat terbelahnya pendapat para akademisi. Sebagian menilai kehadiran AI sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas belajar.
ChatGPT misalnya, terbukti membantu pengajar, membuat paham peserta didik terhadap konsep-konsep yang kompleks. Disajikan ChatGPT dengan bahasa yang mudah dipahami. Juga pemanfaatannya oleh peserta didik, menjawab pertanyaan para pengajar, menyelesaikan tugas-tugas hingga membantu proses penelitian. Namun justru akibat kemampuan itulah, sebagai akademisi menentang penggunaan ChatGPT di lingkungan kampus. Keberadaannya memasung nalar peserta didik.
Promosi AI, yang berlebihanlah yang memicu perdebatan etis itu. Promosi yang mendudukkan AI, sebagai produk ajaib berkemampuan menyelesaikan segala hal dengan benar. Proses penciptaannya seakan tak terjangkau akal pikiran.
Ian Firth, 2023 dalam artikelnya yang berjudul ‘Why the Right Data Input is Key: A Machine Learning Example’, menguraikan, dalam proses penciptaan AI, kualitas dan kuantitas data jadi kata kunci. AI bukanlah black magic, yang proses penciptaannya tak dapat dipelajari.
Pada AI, input data yang memenuhi syarat, maupun pembelajaran yang berkualitas, bertanggungjawab terhadap kinerja algoritma yang tercipta. Ini artinya, manakala kualitas dan kuantitas data, juga pola pembelajaran selama proses penciptaan mesin bervariasi, tergantung pada manusia yang terlibat, kinerja AI yang dihasilkan, tak selalu unggul.
Penjelasan ini dapat dimaknai: dalam proses input data syarat kurasinya terjaga: jumlah minimal data, validitas, etika, hingga sumber data yang jelas, maka mesin akan terlibat dengan data yang memenuhi syarat. Itu saja belum cukup.
Proses yang terjadi pada machine learning ini tergantung pada pelatihan di proses berikutnya, deep learning. Hasilnya berupa algoritma, yang menginteraksikan data pada semesta kemungkinan. Selain tergantung pada spesifikasi perangkat, seluruh proses tergantung pada manusia. Ini dapat dinilai sebagai computer vision, yang mengindikasikan kecerdasan mesin.
Dapat ditarik pemahaman dari uraian di atas, kinerja AI bergantung pada manusia yang terlibat dalam proses penciptaannya. Andaikan terdapat 2 perangkat mesin berspesifikasi sama, namun di salahnya terjadi pembiaran terhadap syarat data yang dimasukkan, sedangkan pada mesin lainnya syarat data terpelihara ketat, akan dihasilkan AI dengan kinerja yang beda. Yang satu AI dengan data yang buruk, lainnya AI dengan data terjaga.
Implikasi seluruhnya, menilai AI tanpa paham proses input data, pelatihan yang diprogramkan, seraya menganggap semua produk AI sama, tak lain menganggap AI sebagai mesin sakti tanpa kesalahan. Menjadikan produknya ~yang kualitas datanya bercampur dan pelatihannya buruk~ sebagai produk akademis, tentu saja tak etis.
Ini karena membiarkan peserta didik, mengkonsumsi produk pembelajaran yang tak jelas kualitasnya. Dalam realitasnya, ada peserta didik di suatu lembaga pendidikan, menerima bahan ajar produk ChatGPT, yang ketika diperiksa akurasi datanya, rendah. Problem etis macam ini, tak dapat dibiarkan meluas.
*) Penulis adalah Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital
**) Tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis, bukan pandangan Urbanasia




