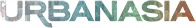Fungsi Konten Mulai Bergeser, Budaya pun Malih Rupa

ENTAH tak jelas bagaimana bergesernya, konten yang pada aneka model komunikasi adalah pesan, hari ini secara budaya mengalami perluasan fungsi. Hal yang paling mungkin jadi pemicu perluasan itu adalah intensifnya pemanfaatan teknologi digital. Akibatnya hampir melepaskan konten dari fungsi asalnya.
Komunikasi konvensional, sebagaimana dikemukakan ilmuwan komunikasi Wilbur Schramm dalam ‘How Communication Works’ (1954), dapat diringkas: semua ide, gagasan, konsep, ditumpukan pada elemen pesan. Berbagai bentuk isi pikiran ini, dimuat pengirim pesan sebagai simbol.
Penggunaan simbol mempertimbangkan kesepakatan budaya. Artinya, walaupun pemuatan isi pikiran menggunakan simbol yang lazim secara budaya, namun proses pemaknaan oleh penerima pesan, bisa berbeda dari maksud pengirim pesan. Ini karena simbol bersifat arbitrar, manasuka: tak terikat ruang dan waktu. Semua yang pernah mempelajari Ilmu Komunikasi secara sistematis, pasti paham pengertian dasar elemen pesan ini.
Hari ini, di tengah pusaran internet culture - istilah yang turut dipopularkan David Silver, 2004 lewat tulisannya Study Internet/Cyberculture/Digital Culture/ New Media/Fill in The Blank - konten mengalami malih fungsi. Ia jadi artefak budaya, pusat aneka peristiwa.
Pertama, konten berfungsi untuk membangun eksistensi diri. Ini kerap jadi pilihan para produsen dan distributor konten. Lewat fungsi ini, secara sistematis maupun tidak, eksistensi terbentuk. Kata kuncinya, produksi terus konten secara konsisten dan distribusikan lewat aneka platform media sosial.
Membangun eksistensi diri lewat cara ini, memang bukan hal baru. Sepanjang sejarah relasi orang dengan media sosial, fungsi dasar konten mampu mengubah no body jadi somebody. Paling tidak, itu akhirnya yang jadi formula andalan di awal kehadiran media sosial. Banyak selebgram, youtuber, selebtwitt, tiktokers yang mengemuka, lantaran memuat secara konsisten konten tentang dirinya. Pengenalan publik yang tercapai lewat cara ini, sering jadi bahasan soal strategi personal branding. Namun tanpa formulasi rumit personal branding pun, konsistensi mampu mengantar orang masuk relung ingatan publik yang istimewa. Eksistensi seseorang lewat konten, menjangkau ingatan publik.
Atas alasan eksistensi pula, orang ditantang dengan berbagai cara, untuk menampilkan dirinya. Ini karena, makin banyak pemakai platform, ruang ingatan publik yang diperebutkan juga makin sempit. Kompetisi menduduki ruang ingatan, jadi warna budaya yang utama. Konten dihadirkan dengan tendensi, memaksa masuk relung ingatan yang sudah sesak. Maka dituntut adanya cara yang harus terus diperbarui.
Namun, walaupun aneka cara tampil lewat konten sudah lazim, publik tetap dibuat terperangah. Ini terjadi manakala ada konten yang terlampau kompetitif. Salah satu contohnya, dapat diperoleh dengan menggunakan kata kunci: selebgram+konten+porno+ig live, di mesin pencari. Dari pencarian, akan ditampilkan berbagai judul berita oleh sedikitnya 10 media yang berbeda. Bahasannya terkait adanya gadis asal Garut yang mengadakan pertunjukan langsung bermedium IG live.
Baca Juga: Gen Z: Tak Hanya Bisa Bikin ‘SCBD’
Konten ini jadi perbincangan, lantaran Sang Gadis mempertontonkan tindakan yang termasuk ketegori asusila. Ia mempertontonkan pornografi. Tentu saja karena merupakan materi yang terlarang menurut UU ITE, pertunjukan sang Gadis jadi urusan polisi setempat. Saat diminta keterangan, selain menjual konten demi sejumlah harga tertentu, pendorong lainnya adalah keinginan untuk jadi selebgram. Memang nyata hasilnya, dalam 2 bulan jalankan aksi, follower gadis ini bertambah 20 ribu orang. Eksistensi berhasil terbangun, walaupun ditempuh lewat cara yang muram. Di sini, konten berfungsi sebagai penarik perhatian. Fungsi kedua.
Fungsi konten ketiga, dengan yang terjadi di Tasikmalaya. Kejadian ini sangat menyesakkan dada. Bahkan dada mereka yang belum pernah jadi orangtua pun. Di kota ini diberitakan, seorang anak meninggal dunia setelah diduga mengalami depresi. Depresi lantaran konten dirinya, dipaksa memperlakukan kucing secara tak manusiawi, beredar lewat media sosial. Teman-temannya memproduksi dan mendistribusi konten itu, dengan cara merundung. Dalam peristiwa itu, sesungguhnya korban bukan hanya anak yang meninggal, tapi teman-teman pelakunya juga korban. Mereka semua adalah korban kompetisi konten. Konten macam ini, berfungsi sebagai material kompetisi.
Dorongan kompetisi terjadi, akibat perebutan perhatian yang makin sulit diperoleh. Ini memaksa produsen dan distributor konten, menemukan aneka cara memanen respons yang berlimpah. Jika nilai konten diilustrasikan sebagai kurva distribusi normal, bentuknya seperti lonceng yang tertelungkup. Sisi kiri lonceng diduduki konten yang paling buruk. Bergerak menuju sisi kanan, sebagai konten yang paling baik. Di tengah-tengahnya adalah konten rata-rata, biasa saja. Sengitnya kompetisi konten terbentuk oleh pasar. Ini terjadi ketika pada kedua ujung lonceng, disediakan ganjaran ekonomi maupun penghargaan sosial.
Penghargaan yang berwujud perhatian. Maka jadi hal yang lazim, ketika nilai ekonomi maupun perhatian diraih oleh konten buruk pun. Keburukannya justru mengundang perhatian yang masif: posisi trending topic, distribusi yang viral, dan ingatan publik yang dipaksa tembus. Konten buruk bernilai ekonomi, setidaknya jadi perbincangan publik. Hal yang sama dialami oleh konten baik. Konten baik jadi ladang respon, dibicarakan dan muara beredarnya iklan.
Baca Juga: Terang-Kelam Dunia Teknologi di Masa Depan
Tinggal memilih, mau memproduksi konten buruk atau baik? Sayangnya dalam proses kompetisi, konten buruk vs konten baik bukan pilihan biner yang manasuka dipilih. Bobot keduanya tak sama. Dalam dunia konten, tak selalu mudah memproduksi konten baik. Perlu konsep tentang baik, proses produksi yang baik, hingga konsistensi yang terpelihara. Dan sayangnya, ketika sebuah konten sudah dianggap baik, maka yang terjadi adalah me too proses. Ditiru dengan cepat dan diproduksi secara masif. Ketika muncul ulasan tentang makanan, segera muncul konten serupa soal makanan. Demikian pula ketika tutorial berdandan jadi ceruk yang menarik, segera menjamur konten tentang berdandan. Banyaknya konten serupa, segera menggesernya dari kanan lonceng ke tengah. Ini tempat konten biasa. Kalaupun ada beda, sebatas aspek peripheral-nya. Ide sentralnya sama.
Lain halnya dengan konten buruk. Mempertontonkan makan mie instan dicampur sabun deterjen, atau memukul-mukul pohon pisang sampai roboh, segera jadi perhatian. Traffic, kesibukan arus interaksinya, laku dijual guna menangguk iklan. Bagi pengembang platform, ramainya interaksi adalah komoditas utama. Soal kualitas bisa ditunda pembicarannya. Tak heran terjadi replikasi logika sesat. Ini nyata ketika serombongan pelajar menghadang laju truk di jalan raya, sementara teman lain memvideokannya jadi konten. Pengemudi yang tak paham skenario produksi konten, tak mengantispasi tindakan di luar nalar ini. Kecelakaan terjadi. Ada pelajar yang tergilas tewas. Kompetisi konten menuntut dosis tindakan tak bernalar, makin naik.
Kembali pada pemahaman komunikasi konvensional. Di sini konten berfungsi identik sebagai pesan. Di dalamnya termuat ide, gagasan maupun konsep. Aneka isi pikiran orang, ditumpahkan sebagai konten. Tujuannya, untuk disampaikan kepada orang lain. Lewat konten terbentuk saling pemahaman. Tapi apa isi pikiran orang, yang saat terjadi kecelakaan bukan menolong korban tapi justru mengabadikannya sebagai konten?
Dalam budaya macam apa orang sekarang hidup, manakala saling pemahaman dibangun lewat konten, yang pengabadiannya lebih diutamakan daripada menyelamatkan nyawa orang? Ini nyata terjadi saat kecelakaan di seputaran traffic light Cibubur. Realita yang mengundang decak kagum Iron Man. Disebut demikian, lantaran seorang penghibur jalanan berkostum pahlawan Marvel itu, menolong banyak korban sementara yang lain lebih tertarik mengabadikan kecelakaan lewat perangkat digitalnya.
Dari fungsi-fungsi konten yang mengalami perluasan, tanpa sadar orang sekarang hidup dalam budaya, yang justru diasingkan oleh konten.
**) Penulis adalah Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital
**) Tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis, bukan pandangan Urbanasia